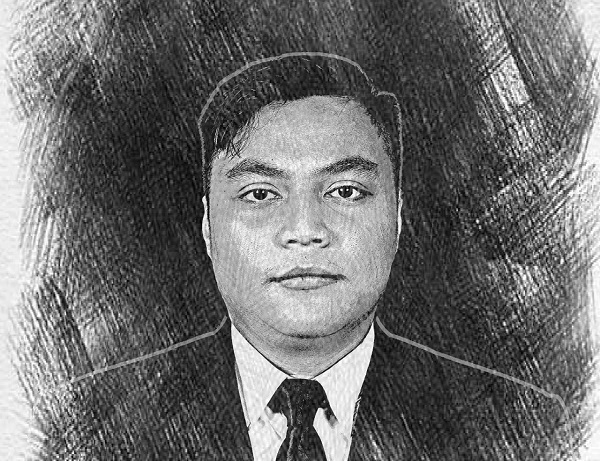JAKARTA – Pada medio Juni 2025, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, sampai ke exit tol di Jawa Barat, badan jalan didominasi oleh truk-truk berat yang berhenti memenuhi area lalu lalang kendaraan. Para sopir truk ini sengaja melakukan aksi parkir massal sebagai bentuk protes dan simbol perlawanan. Alhasil kemacetan terjadi di mana-mana.
Aksi para sopir truk di berbagai daerah tadi karena kebijakan soal Over Dimension Over Load (ODOL) yang membatasi jumlah muatan. Kebijakan ini dicanangkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara sepihak tanpa memikirkan dampak struktural yang akan muncul.
Ketika hukum diterapkan tanpa menyertakan ruang dialog, maka akan menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi yang bisa memperparah keadaan. Kemacetan sebagai efek dari penolakan dari aturan ini muncul ke permukaan, menyebabkan kerugian finansial dengan tertundanya pendistribusian logistik yang dapat mempengaruhi pendapatan pelaku usaha dan negara, baik di pusat maupun daerah.
Di Kabupaten Bojonegoro, 42 truk berat terparkir rapi di ruas jalan nasional Desa Ngulanan, Kecamatan Dander. Klakson-klakson telah berubah menjadi bentuk orasi. Para sopir menuntut pemerintah segera menghentikan razia ODOL yang menurut mereka hanya menjadi alat represi terhadap pelaku usaha kecil. Gerakan ini berlaku masif layaknya terstruktur. Di titik-titik strategis lain seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, sampai Banyuwangi, puluhan hingga ribuan truk berhenti. Suasana mencekam bukan karena kekerasan, tetapi karena negara tak kunjung datang membawa solusi.
Perlawanan ini berlanjut ke Jawa Tengah mulai dari Kudus, Boyolali, Semarang, Batang, Banjarnegara, dan Purbalingga. Suara terdengar lantang dengan narasi yang sama, para Sopir truk bersuara: “Kami ingin patuh, tapi kami tak diberi daya untuk taat.”
Lalu berpuncak hingga ke Jawa Barat, tepatnya di Exit Tol Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, menjadi pusat simbolik dari kelelahan kolektif para sopir truk oleh kebijakan yang begitu jauh dari kenyataan di lapangan.
Legalitas Tanpa Keadilan: Sebuah Pengkhianatan terhadap Rakyat Kecil
Tidak ada yang membantah bahwa kebijakan Zero ODOL memiliki dasar hukum yang tetap. Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah melarang kendaraan yang dimodifikasi melebihi kapasitas dimensi dan daya angkut untuk beroperasi di jalan umum. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 menguatkan hal ini, dan Roadmap
Zero ODOL yang disusun sejak 2020 telah menjadi pijakan implementasi nasional.
Namun pertanyaannya: untuk siapa hukum ini ditegakkan?
Dalam konteks sosial kita, hukum yang diberlakukan tanpa mempertimbangkan ketimpangan ekonomi justru kelak menjadi alat yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pengusaha besar dengan ratusan armada dan dukungan keuangan dapat dengan mudah melakukan
penyesuaian. Tetapi bagi usaha kecil, misalnya pemilik satu truk, yang masih berjuang melunasi cicilan kendaraan dan biaya hidup harian, kebijakan ini menjadi tekanan hidup baru, dan aturan tadi mencekik pengusaha kecil, yang padahal setiap bentuk usaha adalah penggerak roda ekonomi bangsa.
Kita tidak dalam posisi membela sebuah pelanggaran aturan. Kita hanya menuntut proses penertiban dan pemberlakuan kebijakan agar tidak digunakan sebagai alat penindasan.
Negara yang Absen Saat Rakyat Ingin Taat
Berulang kali dalam aksi para sopir, muncul satu narasi yang sama: “Kami ingin taat, tapi kami tak punya alat.” Ini adalah jeritan yang tak pernah dijawab dalam draf kebijakan. Tidak ada skema transisi yang berpihak. Tidak ada dukungan pembiayaan konversi kendaraan. Tidak ada klasifikasi pelanggaran yang memikirkan daya ekonomi mereka. Yang ada hanyalah penindakan, sepihak lewat tindakan Razia. Penahanan, dan Denda. Bahkan dalam beberapa laporan, terdapat dugaan pungutan liar (pungli) yang semakin menambah beban dan minusnya sistem ini. Maka tak heran, bagi sopir truk kecil, hukum terasa seperti jebakan yang disiapkan untuk menindas.
Sopir truk adalah elemen penting dalam ekosistem logistik nasional. Mereka memastikan distribusi bahan pokok, logistik industri, hingga ke pengiriman barang-barang yang sifatnya pokok, dari pelabuhan ke pasar-pasar di desa, bahkan untuk kebutuhan di kota besar pun, memerlukan distribusi lewat armada truk untuk memenuhi keperluan logistik bahan
pokok dan lain-lain. Dalam sistem distribusi logistik, Armada truk adalah jantung yang jarang disorot. Namun justru kepada para sopir truk, negara menyodorkan sanksi tanpa solusi. Tindakan ini mencerminkan tindakan negara yang sering kali terlalu birokratis dalam memahami denyut sosial dan teknokratis dalam menerapkan regulasi.
Jika negara benar-benar berniat menjalankan hukum yang adil, seharusnya tidak hanya berfokus pada penindakan lewat razia, tapi juga memikirkan ulang pola kebijakan logistik nasional, termasuk peran pelaku mikro yang bergerak di akar rumput untuk sistem tersebut.
Perspektif Paralegal: Solusi Harus Diperjuangkan dari Akar
Mohammad Abdul Jabbar, Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Muslimin Indonesia (LBH Sarbumusi) menjelaskan kebijakan hukum seperti ODOL tidak akan cukup jika hanya dijalankan melalui pendekatan represif tanpa memetakan realitas ekonomi rakyat kecil. Negara seharusnya hadir bukan hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga membangun ruang pemulihan struktural bagi warga yang terdampak. Dengan melakukan pendekatan yang lebih edukatif, maka solusi untuk masalah ini akan segera terselesaikan. Negara harus membangun ruang dialog yang sifatnya mengedepankan musyawarah, agar meminimalisir konflik yang terjadi di lapangan.
Dengan berbagai pendekatan itu, maka kebijakan akan disambut baik oleh pihak yang dilibatkan. Menurut Jabbar, hukum yang ditegakkan tanpa keberpihakan pada mereka yang lemah hanya akan menghasilkan ketimpangan. “Negara tidak boleh hanya menertibkan, ia juga harus memulihkan, dengan pendekatan restoratif (restorative justice), maka kebijakan ini akan berhasil,” urainya.
Di sini, penting membangun kerangka kebijakan yang tidak hanya melihat pelanggaran sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai akibat dari kegagalan struktural dari sistem yang dipaksakan. “Saya melihat hukum sebagai alat etis, bukan sekadar aturan. Kalau negara terus menekan dari atas, tanpa mendengar suara yang tumbuh dari bawah, maka ia bukan penegak hukum, melainkan pelanggarnya,” tambahnya.
Keadilan Progresif dan Teguran dari Pemikiran Hukum Kritis
Dalam konteks ini, penting rasanya untuk mengingat gagasan Prof. Satjipto Rahardjo, seorang guru besar dari aliran hukum progresif yang pernah mengatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai aturan yang baku dan formalistik, tetapi harus mampu melayani nilai-nilai keadilan sosial dan kontekstualitas realitas.
Dalam kasus ODOL dan sopir truk, penegakan aturan yang terlalu legalistik tanpa melihat situasi ekonomi dan sosial para sopir justru akan menciptakan kekosongan dalam ruang keadilan. Satjipto di banyak tulisannya selalu mendorong agar hukum bisa hadir sebagai alat pembebasan, bukan sebagai alat penindasan. Artinya, ketika ada rakyat yang kesulitan untuk taat karena kondisi struktural, maka tugas negara adalah memudahkan jalan mereka, bukan justru menutupnya. Gagasan ini menjadi pengingat bahwa hukum tidak boleh kehilangan jiwanya. Ia harus berpihak, bergerak, dan berkembang seiring denyut nadi masyarakat yang dilayaninya. Kebijakan ODOL yang tidak sensitif terhadap suara akar rumput adalah bentuk kegagalan dalam menerapkan prinsip hukum progresif seperti yang diajarkan Satjipto Rahardjo.
Jalan Menuju Keadilan Struktural
Kebijakan ODOL harus dikoreksi bukan dalam semangat pembatalan, tetapi dalam semangat penyelamatan. Negara bisa dan harus menghadirkan solusi yang menyentuh, berikut beberapa saran yang dapat dilakukan:
1. Zero ODOL Masa Transisi:
Penegakan Zero ODOL harus dilaksanakan secara bertahap dengan klasifikasi pelanggaran
berdasarkan skala usaha dan kemampuan teknis. Tidak disamaratakan.
2. Skema Konversi Kendaraan Usaha:
Pemerintah perlu menyediakan program konversi kendaraan bersubsidi atau kredit
ultra-mikro tanpa bunga. Koperasi sopir dan lembaga zakat dapat diajak bekerja sama dalam pembiayaannya.
3. Audit Infrastruktur Jalan Nasional:
Jangan bebani sopir sebagai penyebab utama kerusakan jalan tanpa data. Audit infrastruktur jalan perlu dilakukan secara independen dan terbuka.
4. Dialog Representatif Edukatif:
Pemerintah pusat dan daerah harus membuka ruang dialog periodik yang solutif, dengan
komunitas sopir truk, asosiasi angkutan logistik, dan lembaga pendamping hukum agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar partisipatif.
Kebijakan juga sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan beban distribusi masing-masing daerah. Truk yang melintasi pegunungan, jalur antar kabupaten kecil, atau pengangkut hasil bumi lokal seharusnya diberi pengecualian atau alternatif regulasi yang sifatnya fleksibel. Tanpa melihat hal ini, regulasi akan menjadi beban yang membunuh sistem ekonomi pedesaan.
Saat Truk Berhenti, Hukum Seharusnya Bergerak
Aksi truk mogok oleh para sopir tidak boleh dilihat sebagai gangguan lalu lintas atau sabotase distribusi. Ia adalah refleksi dari kebijakan yang gagal memanusiakan hukum. Kita tidak sedang melihat pelanggaran, kita sedang menyaksikan rakyat kecil yang terpaksa melanggar karena negara
tak memberi mereka ruang dan jalan untuk mematuhi. Hukum tidak boleh menjadi pagar berduri bagi mereka yang miskin. Ia harus menjadi jembatan keadilan yang bisa dilewati semua orang, tak peduli seberapa besar kendaraannya, seberapa kecil hartanya.
Dan karena itulah, hadirnya tulisan ini. Bukan sebagai aksi gugatan, tetapi sebagai bentuk panggilan kemanusiaan: kembalikan hukum pada rakyat. Karena di jalanan yang panas itu, di antara truk-truk yang diam, hukum sedang ditunggu untuk menunjukkan keberpihakannya.
Oleh: Mohammad Abdul Jabbar, Paralegal LBH Sarbumusi